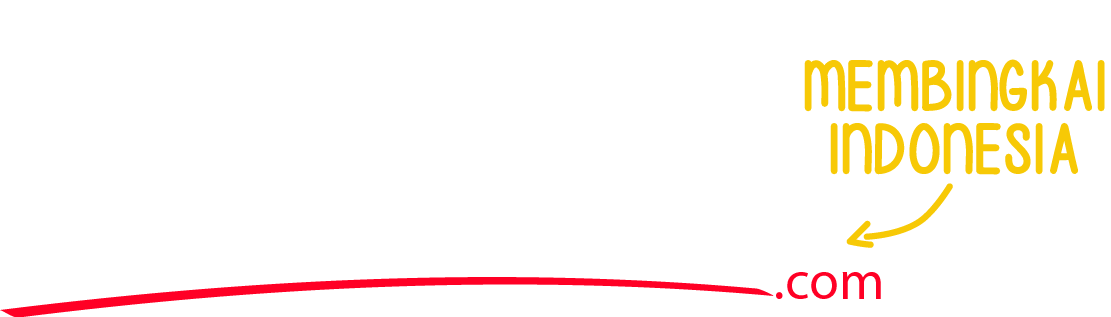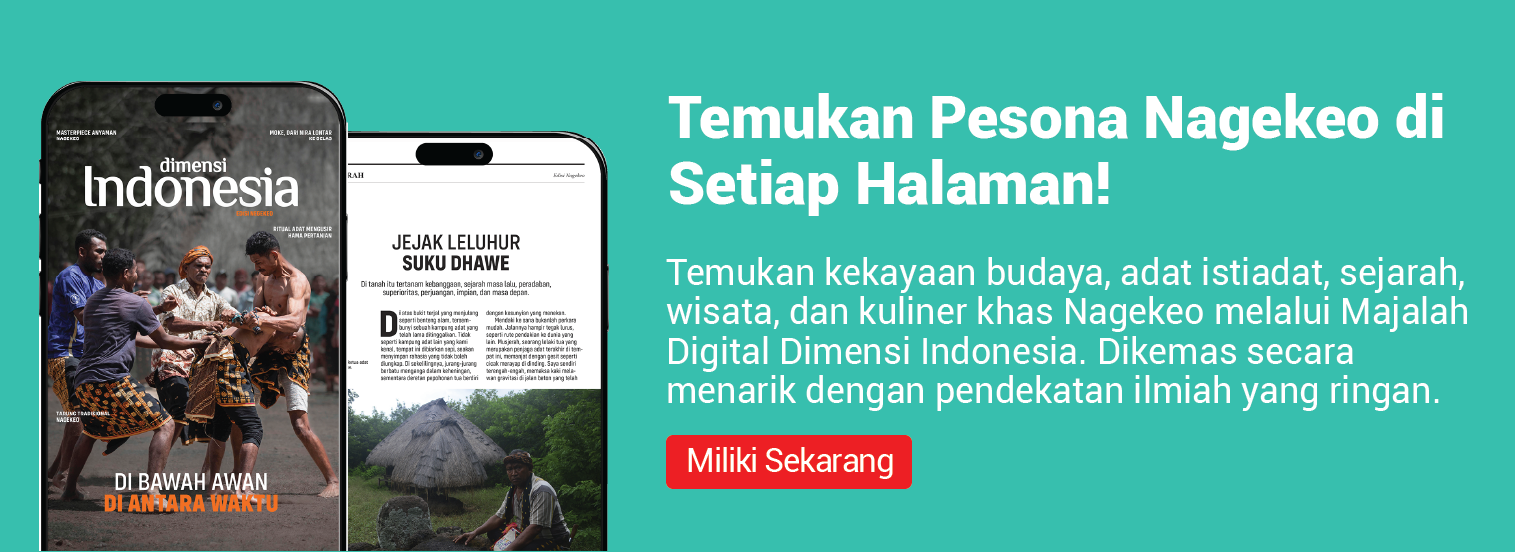Sejak era kolonial Belanda, keindahan kain Sumba telah dikenal luas sebagai salah satu kekayaan budaya yang mengangkat nama pulau ini, selain kuda sandel dan kayu cendana. Kain Sumba dengan nilai estetikanya yang tinggi bahkan dipilih untuk mewakili budaya Indonesia di museum-museum ternama dunia, termasuk di Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat.
Kain tenun Sumba memiliki hubungan erat dengan Marapu, kepercayaan tradisional masyarakat Sumba yang berpusat pada keseimbangan alam dan prinsip dualisme. Nilai ini tergambar dalam ungkapan adat Ina mawolo, Ama marawi — “Ibu menenun, Bapak mencipta” — yang menegaskan peran penting perempuan dalam budaya tenun.
Menenun telah menjadi lambang keutamaan perempuan Sumba. Keterampilan ini berpengaruh pada posisi sosial mereka, di mana perempuan yang mahir menenun dianggap lebih ideal sebagai pasangan hidup. Kain-kain hasil tenunan tersebut bukan hanya digunakan sehari-hari, melainkan juga memegang peran penting dalam berbagai ritual adat, mulai dari kelahiran hingga kematian.

Dalam kepercayaan Marapu, kain tenun juga bisa mewakili kehadiran seseorang. Misalnya, jika seorang ayah tidak dapat hadir saat kelahiran anaknya, kain hinggi miliknya dapat digunakan sebagai lambang kehadiran. Kain juga berfungsi sebagai simbol prestise, alat tukar, hingga ukuran kekayaan seseorang di masyarakat tradisional Sumba.
Kain-kain Sumba, khususnya hinggi (kain pria berukuran besar) dan lau (sarung untuk perempuan), dihiasi oleh motif-motif khas yang kaya makna filosofis. Setiap kampung di Sumba biasanya memiliki motif dan corak warna yang unik. Pewarna alami digunakan, dengan warna dasar kombu rara (merah kecoklatan dari akar mengkudu) dan kaworu (biru tua dari daun tarum).
Motif kain mencerminkan nilai-nilai budaya dan lingkungan sekitar. Di Sumba Barat, motif geometris lebih dominan. Sementara itu, kain dari Sumba Timur menampilkan motif fauna seperti buaya (kekuatan), penyu (kebijaksanaan), lobster (regenerasi), rusa (status bangsawan), kuda (kegagahan), ayam (rumah tangga), burung kakatua (kebersamaan), dan burung merak (keindahan dunia).

Motif lain seperti ana tau menggambarkan manusia dan melambangkan kepolosan, sedangkan motif andung berupa pohon tengkorak, berkaitan dengan tradisi masa lalu tentang kemenangan dalam peperangan.
Beberapa kain juga mengisahkan cerita asal-usul masyarakat Sumba, termasuk legenda tentang pendaratan leluhur di Tanjung Mareha serta sosok mili mongga, makhluk raksasa dalam cerita rakyat Sumba Timur.
Struktur desain kain biasanya tersusun dalam baris-baris, dengan motif utama berada di bagian tengah. Konsep dualisme Marapu tercermin pula dalam pengulangan motif dalam jumlah 2, 4, 8, atau 16, memperkuat makna spiritual kain tersebut.
Walaupun berpijak pada tradisi lokal, tenun Sumba juga mengalami pengayaan dari luar. Hubungan dagang masa lampau memperkenalkan motif naga dari pengaruh keramik Tiongkok, motif singa yang terinspirasi dari era kolonial Belanda, serta motif patola ratu dari pola geometris India, yang hingga kini dihubungkan dengan status bangsawan.

Di balik kemegahan setiap helai kain, ada ketekunan perempuan-perempuan Sumba. Mereka adalah penjaga warisan budaya, memastikan bahwa melalui selembar kain, kisah tentang adat, nilai, dan identitas Sumba tetap hidup dan diteruskan dari generasi ke generasi.
Kain Sumba bukan hanya busana, melainkan medium untuk menyampaikan pesan, nilai, dan sejarah, dalam masyarakat yang sejak lama tidak memiliki sistem aksara tertulis. Melalui wastra inilah, cerita masa lalu tetap dapat berbicara kepada masa depan.