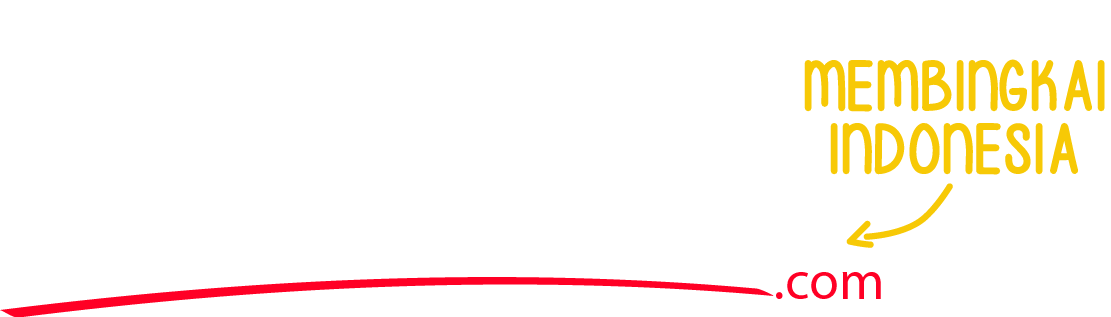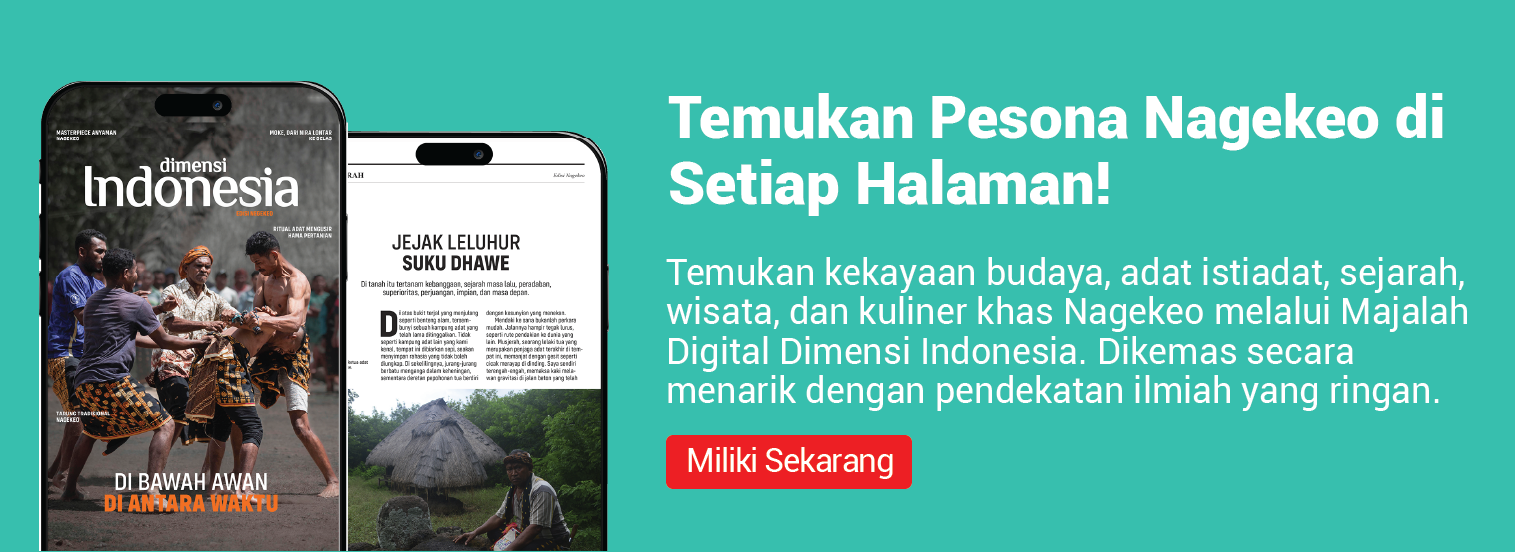Di ujung timur Pulau Jawa, ketika mentari pagi mulai menampakkan sinarnya, Banyuwangi berdiri dalam kesenyapan yang penuh warna. Wilayah ini bukan sekadar pintu gerbang antara Jawa dan Bali.
Ia adalah titik temu kebudayaan, di mana angin dari Bali membawa harum dupa dan gending Hindu, sementara langitnya senantiasa berkumandang azan dan selawat. Banyuwangi, yang dulu dijuluki Blambangan, telah lama menjadi melting pot—perpaduan ragam budaya dan keyakinan yang melebur menjadi satu wajah: khas, hidup, dan magis.
Tak mengherankan bila daerah ini kaya akan kesenian tradisional yang mencerminkan denyut kehidupan masyarakatnya. Tak hanya gandrung yang telah tersohor itu, Bumi Blambangan menyimpan banyak tarian dan pertunjukan yang berakar dari sejarah, spiritualitas, hingga cinta dan perlawanan.
Salah satunya adalah tari jaran goyang. Meski baru muncul di panggung seni pada era 1960-an, tarian ini memiliki daya pikat yang unik karena terinspirasi dari Aji Jaran Goyang, ilmu pelet dalam kepercayaan lokal yang konon mampu membuat seseorang jatuh cinta setengah mati.
Tarian ini ditarikan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memerankan kisah asmara yang diselimuti mistik dan daya magis. Ekspresi wajah yang kuat, gerak tubuh yang ritmis, serta kostum yang terinspirasi dari gandrung dan seblang membuat pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, tapi juga drama yang menggugah rasa. Kini, jaran goyang telah menjadi salah satu ikon kesenian Banyuwangi, bersanding dengan gandrung dalam berbagai festival dan hajatan budaya.
Dari dunia asmara yang magis, kita melangkah ke alam yang lebih purba—barong Using atau yang juga dikenal sebagai barong Kemiren. Di sinilah spiritualitas dan kepercayaan masyarakat Using terjelma dalam rupa seekor makhluk bersayap, dengan wajah gabungan naga dan singa, serta mahkota (mustoko) yang anggun di punggungnya.
Warna merah menyala mendominasi, seakan menjadi simbol perlindungan dari marabahaya. Barong ini bukan sekadar topeng, melainkan entitas sakral yang diyakini sebagai penolak bala. Ia hadir dalam upacara ider bumi atau bersih desa, menari bersama masyarakat, menelusuri jalanan, menyapu segala keburukan yang mungkin mengintai.
Tak jarang, barong Kemiren menari berdampingan dengan tari pitik-pitikan, di mana dua penari berkostum ayam berlaga seperti ayam jago yang sedang bertarung. Sebuah simbol kemenangan, sekaligus hiburan yang memancing gelak tawa.
Namun budaya di Banyuwangi tak hanya berakar pada Hindu dan animisme. Seiring waktu, nafas Islam pun mengisi ruang-ruang keseniannya. Lahir lah hadrah dan kuntulan, tarian yang biasanya dibawakan oleh para remaja perempuan, dengan iringan rebana, selawat, dan nyanyian dalam bahasa Using.
Gerakannya bersimpuh, seolah menggambarkan doa dan ketundukan kepada Sang Ilahi. Kesenian ini awalnya berkembang sebagai media dakwah, namun kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Banyuwangi.
Kuntulan bahkan memiliki cabang dalam bentuk seni bela diri, yang dikenal sebagai variasi dari pencak silat di pesisir utara Jawa. Dengan irama yang menghentak dan pesan-pesan moral yang diselipkan dalam lirik lagu, pertunjukan ini menjadi jembatan antara tubuh, jiwa, dan iman.
Melalui kesenian-kesenian ini, Banyuwangi tak sekadar menyuguhkan pertunjukan. Ia menyampaikan cerita—tentang cinta, tentang leluhur, tentang ketundukan, dan perlawanan. Ia bukan hanya panggung budaya, tetapi juga cermin jiwa masyarakatnya.
Maka bagi siapa pun yang datang berkunjung, menyaksikan kesenian tradisional Banyuwangi bukanlah kegiatan sampingan. Itu adalah pengalaman batin, pelajaran tentang keberagaman yang bersatu dalam harmoni.