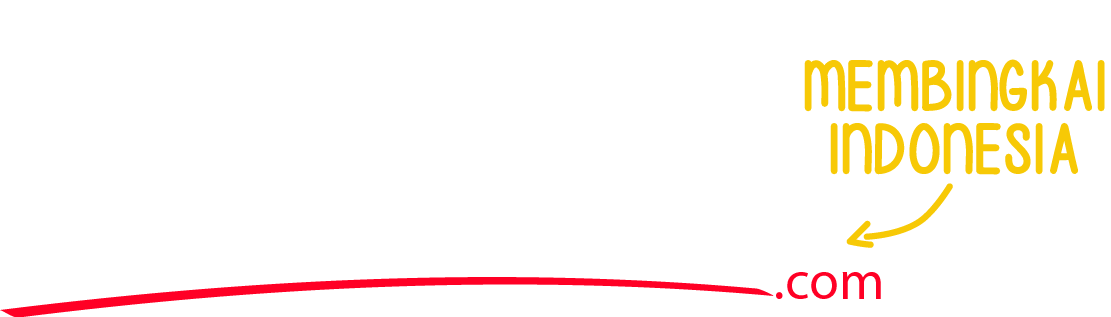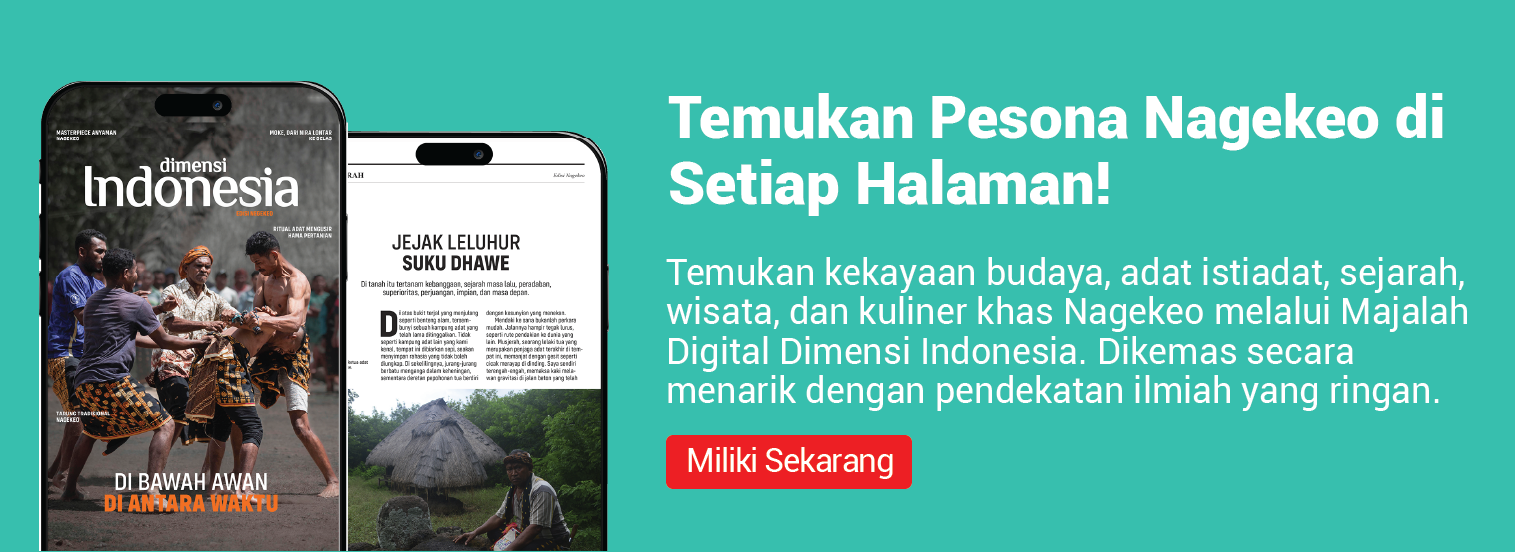Di antara aroma lumpur yang menguar dan denting gamelan yang menggema dari kejauhan, Desa Aliyan di Kecamatan Rogojampi dan Desa Alasmalang di Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, menggeliat dalam suasana sakral.
Setahun sekali, tepatnya di bulan Suro dalam kalender Jawa—yang bertepatan dengan Muharram dalam kalender Islam—dua desa ini menjadi saksi hidup dari sebuah ritual agraris yang unik dan mistis: Keboan dan Kebo-keboan.
Tradisi ini bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan wujud permohonan dan harapan kolektif masyarakat suku Using agar panen mereka kelak diberkahi hasil yang melimpah. Sebagai daerah agraris yang bergantung pada kesuburan tanah dan keberuntungan cuaca, masyarakat percaya bahwa spiritualitas dan ritual memiliki kekuatan tersendiri dalam menentukan nasib sawah mereka. Dan dalam kebudayaan Using, kerbau adalah simbol kesetiaan dan kerja keras dalam siklus pertanian.
Dari segi bentuk, upacara ini menggabungkan elemen mistik, seni, dan nilai gotong royong. Warga desa, terutama para pria terpilih, menjelma menjadi kerbau-kerbau jadi-jadian. Dengan tubuh dilumuri jelaga yang dicampur oli, kepala dihias tanduk buatan dan rambut dari tali rafia atau wig, mereka bertingkah laku layaknya kerbau—menggulingkan tubuh di kubangan, menarik bajak sawah, atau sekadar meringkik seperti hewan ternak.
Namun menjadi “kebo” bukan perkara sembarangan. Di Desa Aliyan, dipercaya bahwa arwah leluhurlah yang menuntun siapa yang layak menjadi kebo, sedangkan di Alasmalang, para tetua adatlah yang menentukan. Para peserta ini seringkali mengalami trance atau kesurupan, yang dalam kepercayaan lokal, menandai keberhasilan komunikasi spiritual dengan dunia gaib.
Proses ritual dimulai jauh hari sebelum hari puncak. Warga bersama-sama membangun gapura dari bambu dan janur yang dihias hasil bumi—sayuran, buah-buahan, dan bunga. Mereka menyiapkan tumpeng dan sajian kenduri, menata panggung wayang, serta merapikan jalur ider bumi—prosesi keliling desa yang bermakna menolak bala dan memohon keselamatan.
Ider bumi menjadi salah satu prosesi penting, diiringi lantunan gamelan, angklung, dan barong, serta seorang wanita yang merepresentasikan Dewi Sri, dewi kesuburan dalam kepercayaan agraris Jawa. Prosesi ini membawa seluruh elemen upacara mengelilingi desa dengan harapan mengusir roh jahat dan mendatangkan keberkahan.
Puncak acara berlangsung di sebuah petak sawah yang telah disiapkan sebagai kubangan. Di sinilah para kebo beraksi. Dengan ditemani pawang, mereka berguling, mencakar lumpur, dan menarik bajak. Sementara itu, benih padi ditaburkan ke kubangan.
Warga lainnya berlomba-lomba mengambil benih itu, diyakini sebagai simbol keberuntungan. Jika tertangkap oleh para kebo, mereka dilempar ke lumpur sebagai bagian dari simbolisasi perjuangan mendapatkan hasil panen.
Malam harinya, ditampilkan wayang kulit dengan lakon Sri Mulih—kisah kembalinya Dewi Sri membawa kesuburan bagi negeri. Pertunjukan ini menjadi penutup yang menyempurnakan keseluruhan rangkaian upacara, mengikat erat makna spiritual, kultural, dan sosial yang dikandung dalam ritual.
Meski kini tradisi Keboan dan Kebo-keboan juga menjadi daya tarik wisata, kesakralannya tetap terjaga. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat berupaya mempertahankan nilai aslinya, menjadikannya bukan sekadar tontonan, tetapi juga ajang edukasi budaya yang memperlihatkan eratnya relasi manusia dengan alam serta keyakinan mereka.