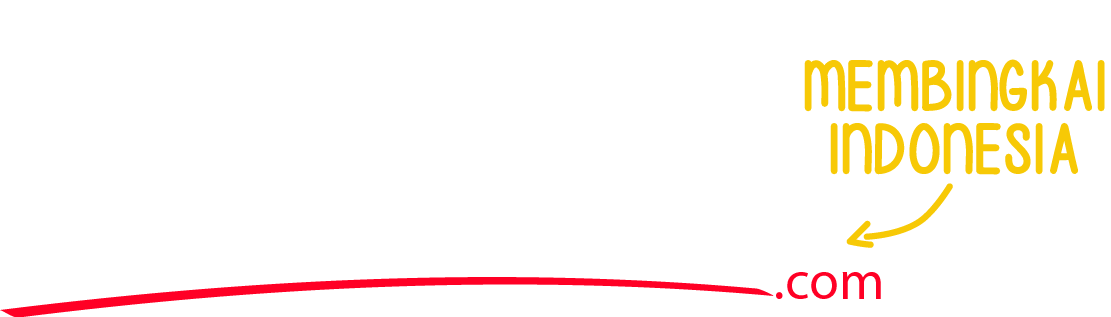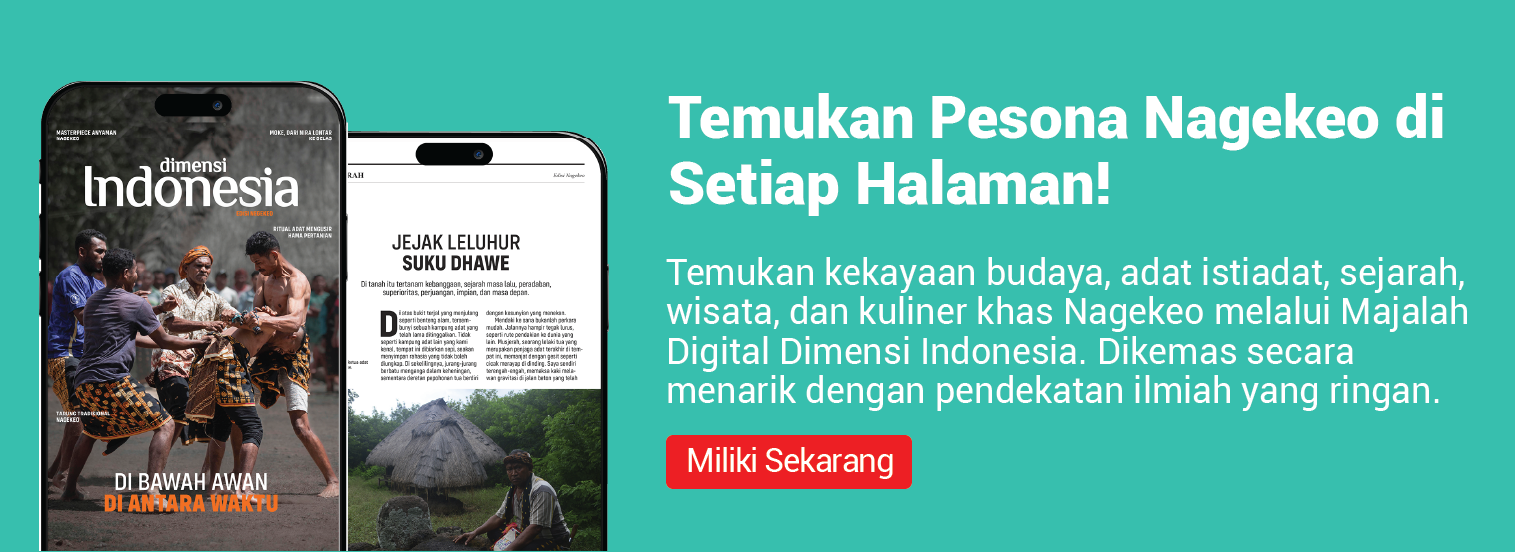Pagi baru saja menyibak kabut tipis di kaki Gunung Ijen saat langkah kaki menapaki jalanan kecil Desa Kemiren. Aroma tanah basah bercampur wangi kayu dari rumah-rumah tua menyeruak dari setiap penjuru. Tapi suara itulah yang lebih dulu menggoda: denting gamelan yang berpadu dengan gemerincing angklung—semacam undangan tanpa kata untuk menyelami denyut kehidupan di desa adat yang tidak pernah benar-benar tidur.
Desa ini bukan sembarang desa. Terletak di Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Kemiren adalah sebuah panggung hidup bagi budaya suku Using, etnis asli Banyuwangi yang tetap teguh berdiri di tengah gempuran modernisasi. Di sinilah tradisi bukan sekadar cerita masa lalu, tapi nadi yang berdetak dalam setiap langkah hari.
Konon, Kemiren tumbuh dari langkah kaki sekelompok suku Using yang menghindar dari cengkeraman kolonial Hindia-Belanda. Mereka menyepi ke dalam hutan, jauh dari urusan birokrasi dan penjajahan. Hutan itu, yang kala itu rimbun oleh pohon kemiri dan duren, menjadi tempat lahirnya desa yang kelak akan menjadi poros budaya Banyuwangi.

Using sendiri dalam bahasa lokal berarti tidak—sebuah kata yang mencerminkan sikap penolakan, perlawanan, dan keteguhan hati. Itulah identitas Wong Blambangan, sebutan lain bagi suku ini, yang dipercaya sebagai penerus Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir yang berdiri gagah di ujung timur Pulau Jawa.
Di Kemiren, rumah bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah simbol. Lihatlah atap-atapnya: Tikel Balung dengan empat sisi, Baresan yang bertiga, hingga Cerocogan yang sederhana. Bangunannya kokoh meski tanpa paku—sebuah teknik arsitektur yang memungkinkan rumah dibongkar dan dipindah seperti menyusun ingatan.
Beberapa rumah kini menjelma jadi galeri seni, kedai kopi, hingga sanggar budaya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Genjah Arum, sanggar yang menggabungkan kopi, seni, dan kisah-kisah tua menjadi satu suguhan penuh rasa. Di sinilah waktu terasa melambat, dan setiap detail mengajak untuk diam, merenung, dan menikmati.
Tiba-tiba, suara musik lain memecah pagi. Kali ini bukan dari gamelan, tapi dari lesung yang dipukul ritmis oleh ibu-ibu. Inilah gedhogan—musik sawah yang tercipta dari aktivitas menumbuk padi, dan kini menjadi pertunjukan penuh jiwa. Di sisi lain desa, angklung paglak dimainkan di atas gubuk tinggi yang berdiri gagah di tepi sawah.
Lihat postingan ini di Instagram
Sore hari, tari-tarian mulai tampil di halaman rumah warga. Gandrung, dengan gerak gemulai dan tatapan tajam, bukan sekadar hiburan. Ia adalah doa, penghormatan, dan sejarah yang menari di atas bumi. Bahkan pengunjung pun dipersilakan belajar menari—karena di Kemiren, budaya bukan untuk dipajang, tapi untuk dihidupi bersama.
Jangan lewatkan juga batik Using—motifnya khas, warnanya teduh, filosofinya dalam. Yang menarik, batik di sini tak digantung di lemari, tapi disimpan dalam toples besar—seperti menyimpan kenangan di dalam tabung waktu. Travelers bisa mencoba mencanting, atau sekadar menatap tangan-tangan terampil yang bekerja dengan cinta.
Dan bila sore mulai turun, waktunya menyeruput kopi khas Kemiren. Di beranda rumah-rumah tua, kopi diseduh perlahan, aroma melayang bersama senyum ramah para tuan rumah. Di sinilah cerita bermula: antara kopi, cerita rakyat, dan senja yang datang seperti puisi.

Sebagai bagian dari Kota Festival, Desa Kemiren juga punya musimnya sendiri. Setiap tahun, desa ini menjadi tuan rumah Festival Ngopi Sepuluh Ewu—seribu cangkir kopi disajikan di sepanjang jalan, menjadikan desa sebagai kedai kopi raksasa di bawah langit. Ada pula Tumpeng Sewu, ritual syukur yang meriah dengan ribuan tumpeng, dan Ider Bumi, prosesi spiritual yang menjaga harmoni desa dan alam.
Desa Kemiren bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah ruang hidup, ruang belajar, dan ruang rasa. Tempat di mana masa lalu, kini, dan nanti saling menyapa. Di sinilah kamu bisa mengalami sendiri apa artinya hidup berdampingan dengan warisan leluhur, bukan dalam museum, tapi dalam napas sehari-hari.