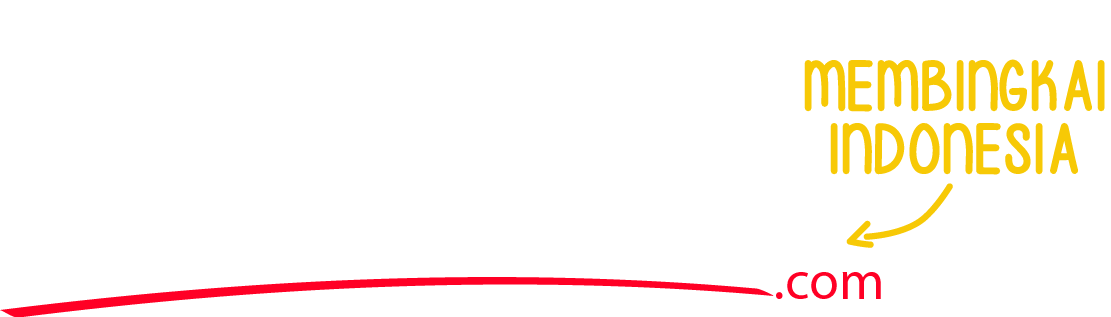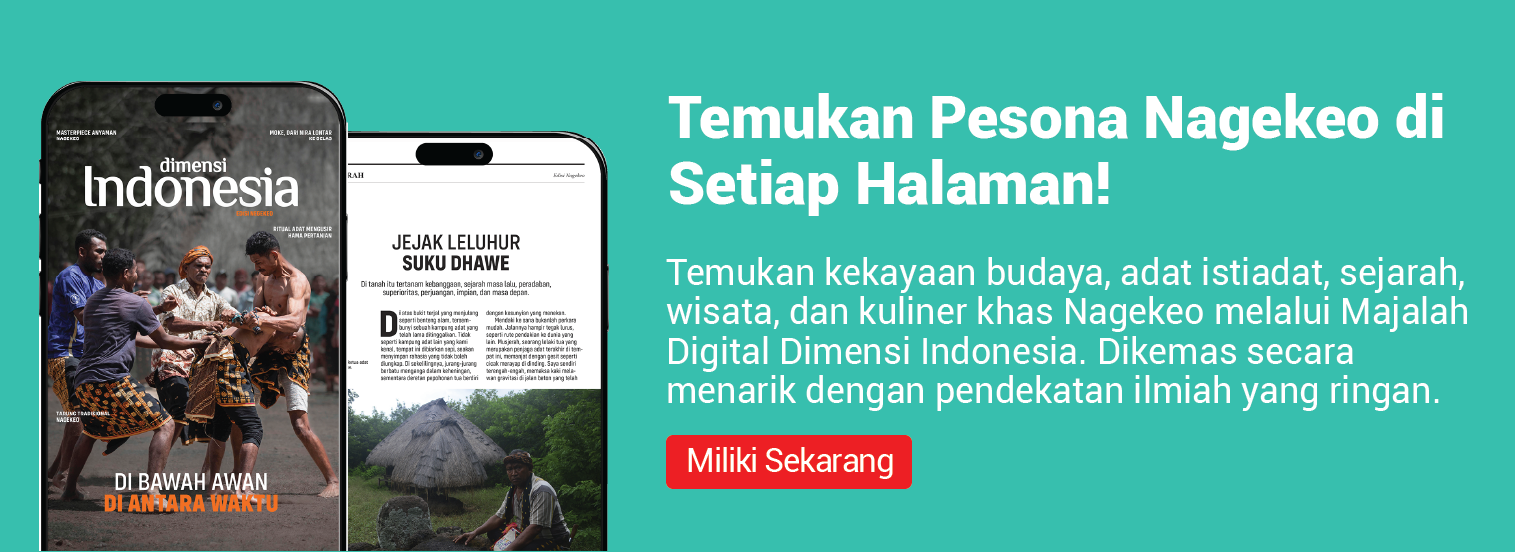Tatkala mentari pagi mulai menyinari sabana Pulau Sumba, denting semangat masa lalu kembali menggema. Di tengah padang rumput luas yang menguning, dua pasukan berkuda berdiri berhadap-hadapan.
Lelaki-lelaki Sumba itu, mengenakan busana adat yang mencolok, menaiki kuda jantan penuh hiasan. Di tangan mereka, lembing kayu digenggam erat. Lalu, dalam satu aba-aba tak terdengar, mereka menerjang. Dan pasola pun dimulai.
Pasola, dari kata sola atau ghola—yang berarti lembing atau kejar dalam bahasa setempat—adalah ritual perang suku yang hanya ada di Sumba bagian barat. Tepatnya di Kodi (Sumba Barat Daya), Lamboya, Wanokaka, dan Gaura (Sumba Barat).
Sekilas tampak seperti arena laga yang penuh kekerasan: lembing dilempar sekuat tenaga, tubuh terguling dari pelana, darah mengucur dari luka. Namun bagi masyarakat Sumba, pasola lebih dari sekadar adu ketangkasan. Ia adalah doa yang bergerak, ritual sakral dalam kepercayaan Marapu.
Pasola hanya berlangsung sekali setahun, menjelang musim tanam padi, biasanya pada Februari atau Maret. Tanggal pastinya tidak pernah pasti. Hanya para rato—tetua adat yang juga pemimpin spiritual—yang dapat menentukan kapan pasola digelar, setelah membaca tanda-tanda alam dan memastikan munculnya nyale, cacing laut yang dianggap pertanda restu leluhur.

Bagi pemeluk Marapu, setiap tetes darah yang tumpah di medan pasola bukan tragedi, tapi persembahan. Darah para kesatria dan kuda dipercaya akan menyuburkan tanah, membawa panen melimpah dan ternak yang berkembang.
Pasola adalah cara masyarakat Sumba memohon ampun, menyampaikan syukur, dan meminta kemakmuran. Di sinilah kekerasan menjadi bagian dari ritual spiritual yang sangat dalam maknanya.
Masyarakat percaya, luka dalam pasola bukan kebetulan. Ia adalah “jawaban” atas perilaku hidup. Bahkan jika sampai ada korban jiwa, itu dianggap sebagai akibat pelanggaran tabu adat—sebuah ganjaran dari alam dan leluhur.
Asal-usul pasola hadir dalam beragam versi. Di Kodi, cerita rakyat menyebutkan bahwa pasola merupakan bentuk syukur kepada Inya Nale, dewi kesuburan yang menjelma menjadi nyale dan menyelamatkan manusia dari kelaparan.
Sementara di Sumba Barat, kisahnya lebih bersifat cinta dan persaingan: tentang Umbu Dulla dari Waiwuang dan Teda Gaiparona dari Kodi, dua pria yang berebut wanita bernama Rabu Kaba. Untuk menghindari perang sungguhan, dibuatlah duel terhormat antar kampung—yang kemudian berkembang menjadi tradisi pasola.

Jika pasola terdengar seperti extreme sport, itu karena memang benar adanya. Setiap kesatria harus memiliki keterampilan luar biasa dalam berkuda, refleks cepat, dan kemampuan melempar lembing secara presisi.
Mereka harus memilih kuda yang berani dan gesit, menjaga keseimbangan sambil menghindari lemparan musuh. Tapi ada aturan adat yang ketat: lembing tidak boleh tajam, tidak boleh menyerang lawan yang jatuh, dan tidak boleh membawa dendam pribadi ke medan laga. Lembing yang jatuh ke tanah? Tidak boleh diambil kembali.
Pasola selalu disaksikan ribuan orang. Tidak ada medan pasola yang sepi. Tiap pertempuran menjadi ajang berkumpulnya kabisu—klan, kampung, bahkan kerabat jauh yang kembali pulang. Suasana ramai, penuh sorak dan degup jantung.
Bagi masyarakat Sumba, pasola adalah identitas, pertunjukan persahabatan, dan cara menjaga silaturahmi antarkampung. Bahkan hingga hari ini, pasola tetap menjadi magnet yang menyatukan masyarakat dalam satu ikatan sejarah dan budaya.