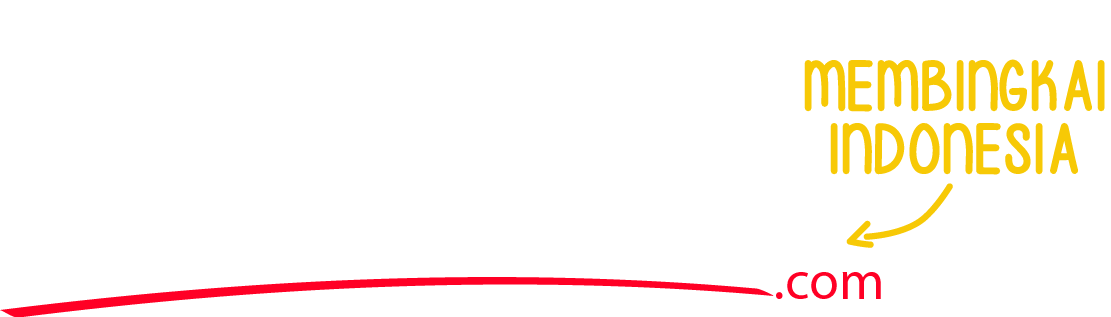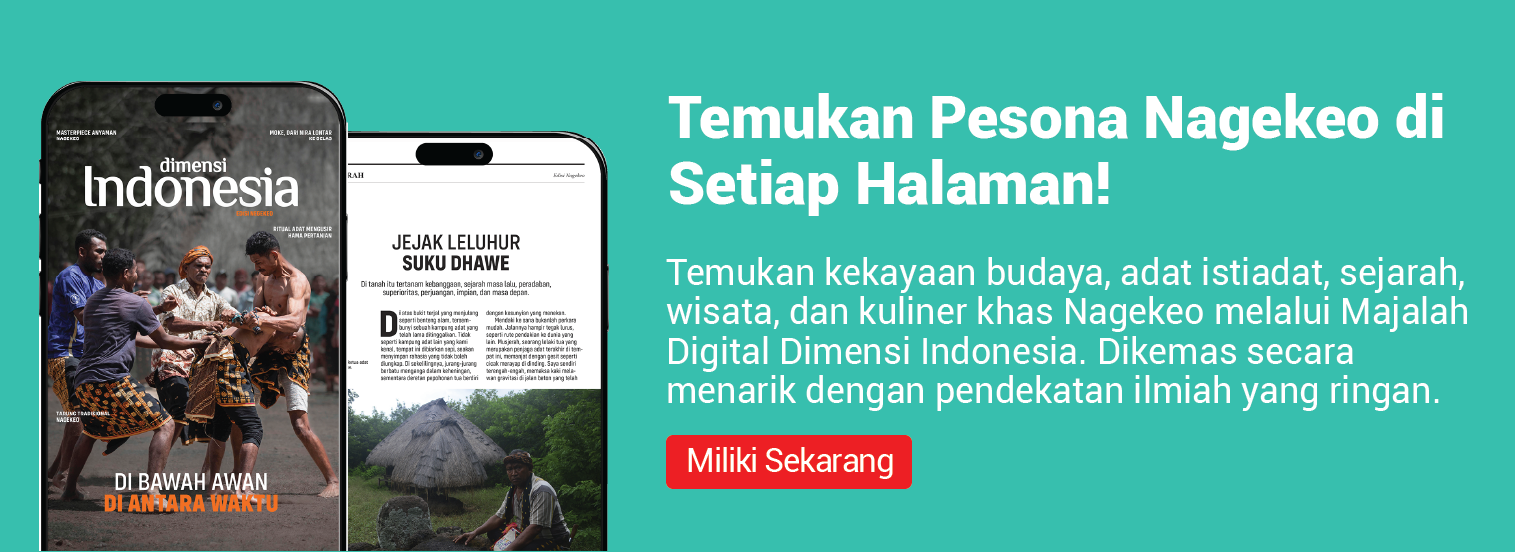Transformasi Menjadi Kesultanan
Sekitar tahun 1605, Gowa–Tallo memeluk Islam melalui dakwah para mubalig dari Minangkabau. Tak butuh waktu lama, seluruh struktur kerajaan dan masyarakat mengikuti, dan sejak itulah Gowa–Tallo lebih dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan kerajaan, mempengaruhi ekspansi wilayah dan penyebaran dakwah ke daerah-daerah Bugis seperti Bone, Soppeng, dan Wajo.
Kesultanan Makassar pun menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan: Ternate, Demak, Banjar, Johor, bahkan Inggris dan Portugis. Namun, langkah ini menimbulkan kecurigaan dari VOC Belanda, yang sedang giat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara.
Perang Makassar dan Kejatuhan Benteng

Ketegangan dengan VOC memuncak dalam Perang Makassar (1666–1669), dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, sosok kharismatik yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Perang ini menjadi salah satu konflik paling sengit antara kekuatan lokal dan kolonial.
Selama bertahun-tahun, Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan dengan strategi militer yang brilian, namun pada akhirnya Belanda memaksa Makassar menandatangani Perjanjian Bungaya (1667), mengakhiri perang dan mempersempit kekuasaan Makassar.
Benteng Somba Opu jatuh dua tahun kemudian. Pusat pemerintahan berpindah ke Benteng Jumpandang, yang kemudian diganti nama oleh Belanda menjadi Fort Rotterdam. Sebagian besar armada dan wilayah Kesultanan diserahkan, namun semangat perlawanan tidak pernah benar-benar padam.
Warisan yang Tak Padam
Kejayaan Kesultanan Makassar tidak berakhir dengan kekalahan. Tahun 1936, Raja Gowa ke-35, I Mangngi Mangngi Daeng Mattutu, membangun istana baru di Sungguminasa, Gowa. Kini dikenal sebagai Museum Balla Lompoa atau Rumah Kebesaran, bangunan ini menyimpan mahkota, batu mulia, naskah lontara, hingga senjata-senjata yang digunakan saat perang. Di dekatnya berdiri Istana Tamalate, simbol arsitektur klasik Makassar yang dibangun pada 1980-an.
Situs-situs sejarah lain yang masih bisa dikunjungi adalah Masjid Katangka, Makam Raja-raja Tallo, serta Benteng Rotterdam dengan Museum La Galigo-nya. Semua menyimpan potongan-potongan sejarah tentang kerajaan yang pernah menantang dominasi kolonial.
Dan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Kesultanan Makassar mengakhiri perannya sebagai entitas politik. Pada tahun 1946, Raja Gowa ke-36, Andi Idjo, menyatakan bahwa kerajaan bergabung dengan Republik Indonesia.
Namun warisan Kesultanan Makassar tetap hidup. Tidak hanya lewat situs sejarah, tetapi juga dalam narasi besar tentang bagaimana kekuatan agraris dan maritim bisa bersatu, mengembangkan diplomasi, melawan kolonialisme, dan menyatukan beragam etnis dan kepercayaan dalam sebuah kerajaan besar di jantung Indonesia Timur.