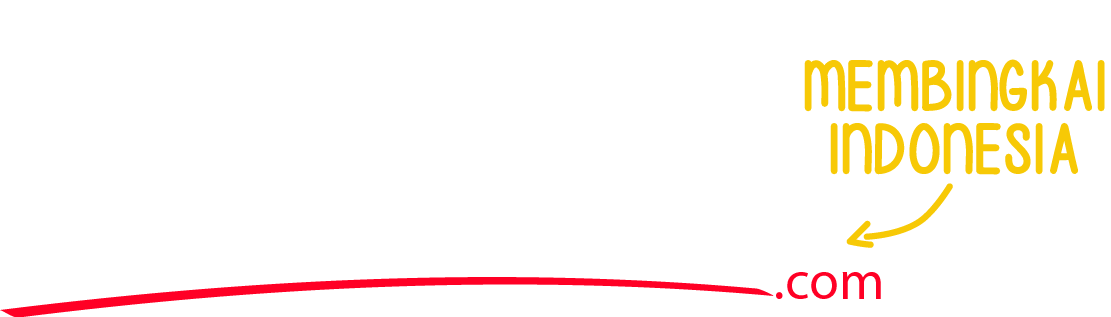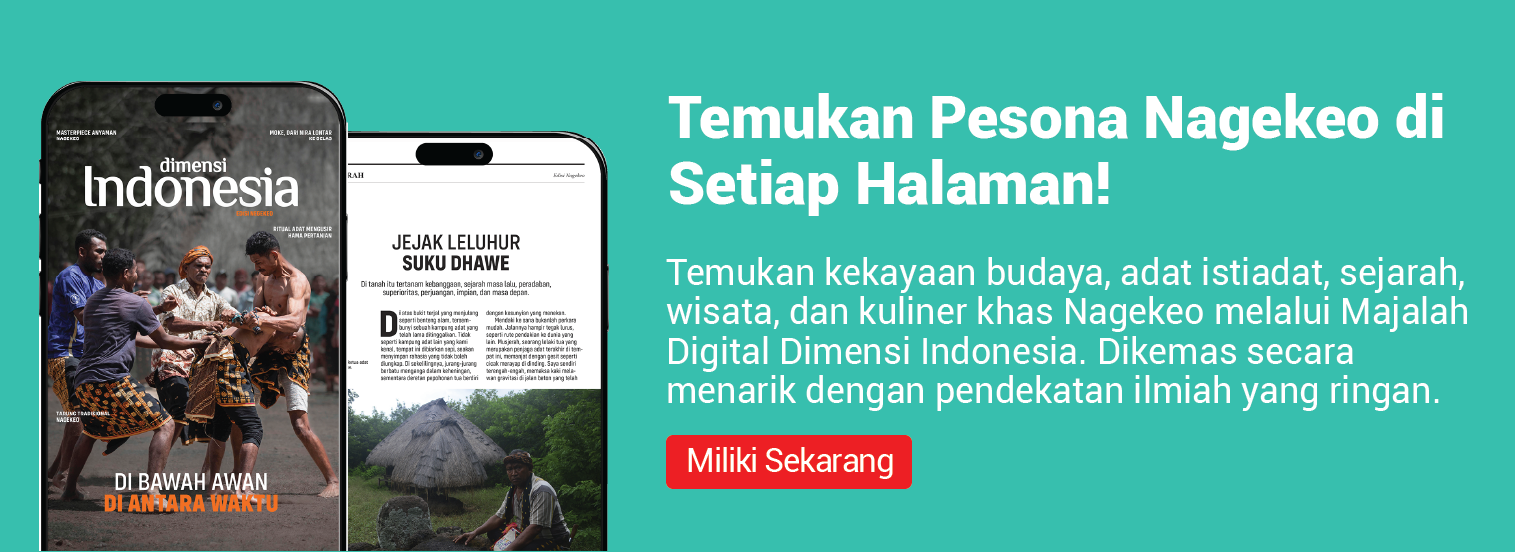Saat fajar mulai menyapu langit timur Pulau Jawa, sebuah patung di Watu Dodol menjadi saksi pertama datangnya cahaya pagi. Di bibir Selat Bali yang biru, patung itu berdiri anggun—seorang penari gandrung dengan mahkota megah dan selendang yang seolah hendak bergerak ditiup angin laut.
Ia bukan sekadar karya seni; ia adalah lambang jiwa Banyuwangi, ikon budaya yang tak lekang oleh zaman. Sejak dibangun pada 2004, patung ini seolah mengingatkan setiap mata yang memandang: inilah tanah di mana tari gandrung bukan hanya kesenian, tapi kehidupan.
Gandrung memang bukan sekadar tarian. Ia tumbuh dari denyut masyarakat Using, suku asli Banyuwangi yang hidup selaras dengan tanah dan warisan leluhur. Dalam bahasa Jawa maupun Indonesia, kata gandrung berarti tergila-gila karena cinta.
Maka tak heran bila penari gandrung, dengan lirikan mata yang tajam dan senyum menggoda, mampu membuat penonton terpesona, bahkan terpikat tanpa sadar. Di berbagai hajatan, dari yang paling resmi hingga yang paling merakyat, gandrung selalu hadir—sebagai suguhan utama, sebagai doa, atau sebagai pengingat akan siapa diri mereka sebenarnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Namun tak banyak yang tahu bahwa tarian yang kini ditarikan di panggung-panggung megah itu sesungguhnya berasal dari ritual tua, bahkan mistis. Sebelum menjadi tarian hiburan, gandrung diyakini lahir dari seblang, sebuah ritual sakral untuk memohon keberkahan Dewi Sri menjelang musim panen. Dalam ritual itu, seorang penari yang telah “kejimen” atau kerasukan akan menari dan melempar selendangnya ke arah penonton.
Siapa pun yang menerima selendang itu harus ikut menari, menjadi bagian dari semacam trance kolektif yang suci sekaligus menghibur. Unsur interaksi ini pula yang diwarisi gandrung: penari akan memilih penonton, bahkan tamu kehormatan, untuk ikut ngibing di tengah lantunan musik yang riuh.
Ada pula kisah lain, lebih kelam dan heroik, tentang kelahiran gandrung. Sebuah cerita lisan menyebutkan bahwa tarian ini dulu digunakan untuk mengecoh penjajah. Penari gandrung akan memikat para serdadu dengan pesona dan minuman, lalu secara diam-diam menghabisi mereka dengan pisau yang tersembunyi di balik kipas.
Di versi lain, gandrung lahir dari pelarian orang-orang Using yang menolak tunduk pada Belanda. Mereka menciptakan kesenian sebagai alat bertahan hidup, menari dari kampung ke kampung untuk ditukar dengan beras dan makanan.
Ver esta publicación en Instagram
Uniknya, gandrung dulu hanya ditarikan oleh remaja laki-laki. Tapi ketika pengaruh Islam mulai mengakar kuat di akhir abad ke-19, peran itu perlahan diambil alih oleh perempuan. Sejak saat itulah gandrung menjadi identik dengan kelembutan dan keanggunan wanita. Bahkan, dulu hanya perempuan dari garis keturunan penari gandrung yang boleh menarikan tarian ini—sebuah tradisi yang diwariskan dari praktik dalam ritual seblang.
Lihatlah kostum penari gandrung: omprog atau mahkota suci yang menghiasi kepala mereka bukan sekadar hiasan, melainkan simbol warisan spiritual. Musik yang mengiringi pun bukan sembarang gamelan. Denting kluncing—alat musik segitiga yang juga dijadikan alat banyolan—beradu cepat dengan kendang, biola, angklung, dan gong. Irama yang naik turun seperti napas penari yang terus menari tanpa henti.
Pertunjukan gandrung biasanya terbagi dalam tiga babak. Dimulai dari jejer, di mana penari menyambut hadirin dengan gerak dan nyanyian. Lalu berlanjut ke paju atau ngibing, saat selendang dilemparkan dan tamu diajak menari.
Lihat postingan ini di Instagram
Babak ini yang paling meriah, penuh tawa, tepuk tangan, dan terkadang saweran. Setelah semua puas, pertunjukan ditutup dengan seblang subuh—bagian yang paling sunyi dan khidmat. Lagu-lagu dilantunkan dengan pelan dan penuh penghayatan, seolah menjadi doa perpisahan sebelum pagi benar-benar datang.
Kini, gandrung bukan hanya milik panggung desa. Ia telah mendunia. Sejak 2011, ribuan penari berkumpul tiap tahun dalam Gandrung Sewu Parade—tarian massal yang diadakan di pinggir laut Banyuwangi. Tahun 2018, Taman Gandrung Terakota pun dibuka. Ratusan patung penari tersebar di hamparan sawah hijau, menciptakan lanskap budaya yang tak hanya memesona mata, tapi juga menggugah hati.